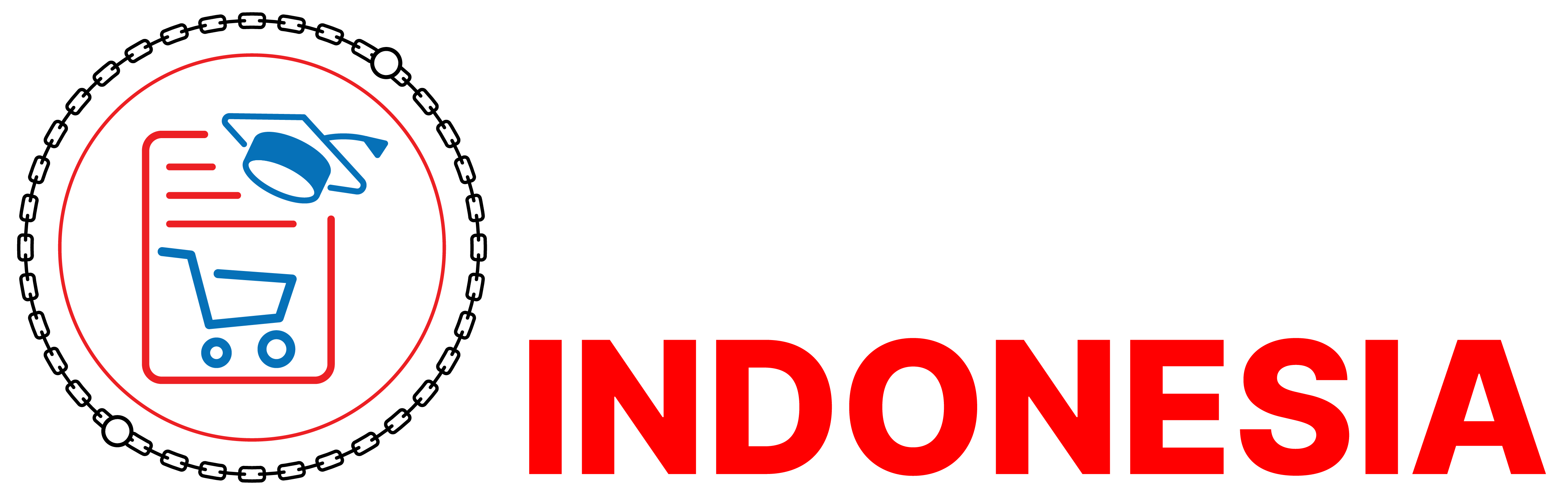I. Pendahuluan
Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, PPK memegang peran penting sebagai penentu kebijakan teknis dan administratif kontrak. Namun, dalam praktiknya, ketidaksesuaian pelaksanaan oleh PPK-baik berupa pembayaran tertunda, penarikan jaminan pelaksanaan secara sepihak, hingga pembatalan kontrak sepihak tanpa dasar hukum-sering menyebabkan kerugian vendor. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan: “Bisakah vendor menggugat PPK secara hukum?”
Artikel ini menyajikan penjelasan panjang dan mendalam mengenai dasar hukum, hak vendor, proses hukum baik administratif maupun litigasi, risiko dan strategi mitigasi, hingga contoh kasus nyata. Dengan ulasan ini, vendor diharapkan memiliki panduan komprehensif untuk menegakkan haknya secara profesional dan legal.
II. Dasar Hukum dan Peran PPK
Dalam struktur pengadaan barang/jasa pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peran sentral yang sangat krusial. PPK bukan sekadar pelaksana teknis, tetapi juga menjadi pihak yang memegang kuasa atas aspek hukum, keuangan, hingga pelaksanaan fisik dari suatu kontrak pengadaan. Keberadaan dan kewenangan PPK diatur secara eksplisit dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
Berdasarkan regulasi tersebut, PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk:
- Menyusun dan menetapkan perencanaan pengadaan,
- Menandatangani kontrak dengan penyedia,
- Mengelola administrasi pelaksanaan kontrak,
- Mencairkan pembayaran sesuai tahapan yang telah disepakati dalam kontrak.
PPK berfungsi sebagai penanggung jawab langsung pelaksanaan kontrak, dan bertanggung jawab secara hukum atas segala keputusan administratif yang dibuat selama proses pengadaan.
Namun dalam praktiknya, tidak sedikit vendor yang merasa dirugikan oleh keputusan PPK yang dianggap tidak adil, tidak profesional, atau bahkan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Bentuk tindakan yang bisa digugat, antara lain:
- Pemutusan kontrak secara sepihak tanpa dasar atau tanpa peringatan.
- Keterlambatan pencairan pembayaran melebihi tenggat waktu yang diatur, yaitu 14 hari kerja setelah dokumen pembayaran lengkap.
- Pencairan jaminan pelaksanaan secara sepihak tanpa pemberitahuan atau pemeriksaan bersama.
- Perubahan lingkup pekerjaan tanpa adendum resmi.
- Penetapan blacklist vendor tanpa dasar atau tanpa melalui klarifikasi.
Vendor yang merasa dirugikan oleh tindakan seperti ini dapat mengajukan keberatan atau bahkan gugatan formal terhadap PPK. Dasar gugatan tersebut bertumpu pada prinsip legalitas administratif, di mana setiap tindakan pejabat publik (termasuk PPK) wajib tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Gugatan terhadap PPK dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika vendor dapat membuktikan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk keputusan tata usaha negara (KTUN), yakni:
- Keputusan tertulis,
- Dikeluarkan oleh pejabat administrasi negara,
- Bersifat konkret, individual, dan final,
- Menimbulkan akibat hukum bagi vendor sebagai pihak yang terkena dampak.
Selain itu, vendor juga bisa memulai proses melalui pengaduan administratif kepada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), Ombudsman Republik Indonesia, atau melalui mekanisme keberatan internal di instansi yang bersangkutan. Langkah ini penting dilakukan sebelum masuk ke pengadilan, sebagai bagian dari prinsip penyelesaian berjenjang dan upaya exhaustion of remedies.
III. Hak Vendor dan Syarat Gugatan
Sebelum melayangkan gugatan terhadap PPK ke lembaga peradilan administratif atau lainnya, vendor harus memastikan bahwa syarat-syarat formal dan substantif terpenuhi. Hal ini penting untuk memperkuat posisi vendor di hadapan hukum, dan menghindari penolakan perkara karena gugatan dianggap prematur atau tidak berdasar.
- Kepastian formal:
Vendor harus menunjukkan bahwa telah menempuh upaya administratif internal terlebih dahulu. Ini dapat berupa:- Surat klarifikasi atau permintaan penjelasan kepada PPK.
- Somasi resmi yang berisi peringatan untuk memperbaiki tindakan.
- Pengaduan ke unit pengadaan atau atasan langsung PPK.
Langkah ini menunjukkan bahwa vendor telah beritikad baik untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menempuh jalur hukum.
- Kerugian nyata:
Vendor perlu membuktikan bahwa tindakannya didasarkan pada kerugian konkret yang timbul akibat keputusan PPK. Contoh kerugian nyata meliputi:- Kerugian finansial karena termin pembayaran tertunda tanpa alasan jelas.
- Kehilangan hak tender akibat masuk blacklist secara tidak sah.
- Kerusakan reputasi usaha yang berdampak pada relasi bisnis lain.
- Kerugian atas biaya produksi atau pembelian barang yang tidak dibayar.
Dokumen yang diperlukan biasanya berupa kontrak, addendum, invoice, dokumen serah terima (BAST), dan korespondensi tertulis dengan PPK.
- Dasar hukum kuat:
Vendor harus menunjukkan bahwa tindakan PPK bertentangan dengan hukum positif, antara lain:- Pelanggaran terhadap Perpres 12/2021.
- Tidak sesuai dengan isi kontrak atau ketentuan LKPP.
- Melanggar asas-asas pemerintahan yang baik: akuntabilitas, keterbukaan, dan profesionalisme.
Tanpa dasar hukum yang kuat, gugatan akan dianggap lemah dan dapat ditolak di awal pemeriksaan.
- Ketentuan TUN (Tata Usaha Negara):
Vendor harus memastikan bahwa objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). KTUN adalah keputusan tertulis oleh pejabat negara dalam lingkup wewenangnya, yang bersifat final dan berdampak hukum individual terhadap vendor.
Contoh KTUN yang dapat digugat:- Surat pemutusan kontrak sepihak.
- Surat pencairan jaminan pelaksanaan.
- Penetapan vendor sebagai daftar hitam.
- Penolakan pembayaran termin padahal dokumen lengkap.
Hak vendor juga mencakup pengembalian dana jaminan, pencairan pembayaran termin, kompensasi atas kerja yang sudah dilakukan, atau rehabilitasi reputasi apabila vendor masuk daftar hitam secara tidak sah.
IV. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-Litigas
Meskipun jalur gugatan hukum terbuka, dalam praktiknya vendor disarankan terlebih dahulu menempuh berbagai mekanisme penyelesaian non-litigasi. Hal ini tidak hanya lebih cepat dan hemat biaya, tetapi juga berpotensi menjaga hubungan baik antara penyedia dengan instansi pemerintah.
- Negosiasi langsung:
Vendor dapat meminta pertemuan atau klarifikasi langsung dengan PPK atau tim pelaksana proyek. Negosiasi bisa melibatkan:- Penjadwalan ulang pekerjaan.
- Penyelesaian keterlambatan pembayaran.
- Koreksi terhadap keputusan pemutusan kontrak yang belum didukung dokumen kuat.
- Mediasi internal: Jika negosiasi tidak membuahkan hasil, vendor dapat meminta mediasi dari unit pengadaan, biro hukum, atau bahkan Sekretariat Jenderal instansi. Mediasi memungkinkan kedua belah pihak menyampaikan argumen dan menyepakati jalan tengah tanpa formalitas pengadilan.
- Kesepakatan administratif:
Jika mediasi berhasil, maka dapat dibuat Berita Acara Kesepakatan yang mengikat secara hukum administratif. Isinya bisa berupa:- Pencairan sebagian termin sebagai goodwill.
- Pembatalan blacklist dan pemulihan hak vendor.
- Revisi jaminan pelaksanaan atau pemberian waktu tambahan (extension of time).
Namun, jika tidak ada penyelesaian internal yang memuaskan, vendor dapat melanjutkan ke PTUN untuk menggugat keputusan PPK berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan. PTUN biasanya lebih cepat dari litigasi pidana/perdata, fokus pada aspek legal administratif, dan memberikan kekuatan hukum eksekusi terhadap keputusan yang dinyatakan batal atau tidak sah.
V. Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
- Syarat dan Objek Gugatan
Salah satu jalur formal yang dapat ditempuh oleh vendor ketika merasa dirugikan oleh keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun, penting dipahami bahwa tidak semua jenis sengketa pengadaan dapat langsung dibawa ke PTUN. Hanya keputusan yang dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bisa digugat. KTUN adalah keputusan tertulis yang bersifat final, dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan, dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang bersangkutan. Contoh KTUN yang lazim disengketakan vendor meliputi:
- Surat resmi pencabutan kontrak sepihak oleh PPK tanpa alasan yang kuat atau tanpa tahapan sanksi administratif.
- Surat pencairan jaminan pelaksanaan karena dianggap wanprestasi, padahal vendor belum diberi kesempatan membela diri.
- Penetapan daftar hitam (blacklist) yang diumumkan melalui media resmi LPSE atau instansi.
Vendor wajib memastikan bahwa keputusan tersebut memang bersifat final dan memiliki kekuatan hukum administratif, bukan sekadar korespondensi biasa atau teguran internal. Selain itu, vendor harus dapat membuktikan bahwa keputusan tersebut mengakibatkan kerugian nyata dan langsung terhadap bisnisnya, baik berupa kehilangan hak kontraktual, reputasi usaha, maupun kerugian materiil.
Gugatan harus diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 90 hari kalender sejak vendor secara resmi menerima atau mengetahui isi keputusan tersebut. Tenggang waktu ini sangat penting, karena apabila dilampaui, maka gugatan akan ditolak secara formil tanpa diperiksa substansinya.
- Prosedur Pengajuan
Langkah pertama yang harus dilakukan vendor adalah menyusun gugatan secara tertulis, ditujukan kepada Ketua PTUN di wilayah hukum tempat instansi atau PPK berada. Gugatan harus memuat:
- Identitas lengkap penggugat (nama perusahaan, alamat, NPWP, akta perusahaan, dan perwakilan hukum).
- Objek sengketa secara rinci, termasuk salinan surat keputusan yang digugat.
- Uraian tentang fakta-fakta yang melatarbelakangi gugatan.
- Dalil hukum yang menjadi dasar gugatan (pelanggaran prosedur, cacat yuridis, atau penyalahgunaan wewenang).
- Permintaan atau petitum, seperti permohonan pembatalan KTUN, perintah mengembalikan hak kontraktual, atau pemulihan nama baik vendor.
Dokumen pendukung sangat penting, seperti kontrak, bukti komunikasi, surat somasi atau keberatan, serta bukti kerugian (invoice, mutasi rekening, atau kehilangan peluang usaha).
Vendor juga harus membayar biaya perkara yang ditentukan berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung, biasanya berkisar antara 1-2% dari nilai sengketa atau sesuai dengan klasifikasi gugatan ringan atau sedang. Setelah diterima, gugatan akan didaftarkan secara resmi dan diberi nomor perkara.
- Sidang PTUN
Sidang PTUN terdiri dari beberapa tahap. Sidang pertama bersifat administratif, yaitu untuk memverifikasi kelengkapan dokumen dan legal standing penggugat. Bila dokumen lengkap, maka sidang masuk ke tahap pemeriksaan pokok perkara.
Pada tahap ini, hakim akan memeriksa legalitas dari keputusan PPK yang disengketakan. Apakah keputusan tersebut dikeluarkan sesuai prosedur yang ditentukan dalam regulasi pengadaan? Apakah asas-asas pemerintahan yang baik (legalitas, akuntabilitas, transparansi) telah dijalankan? Dan apakah vendor benar-benar mengalami kerugian?
Hakim juga dapat memanggil saksi ahli, meminta keterangan tambahan, atau bahkan melakukan pemeriksaan setempat jika dianggap perlu. Proses ini bisa berlangsung 2-4 bulan tergantung kompleksitas perkara.
Putusan dapat berupa:
- Pembatalan KTUN sehingga status vendor dipulihkan.
- Perintah agar instansi membayar termin yang ditunda.
- Pembatalan status blacklist dan perintah pemulihan nama baik vendor.
- Atau penolakan gugatan jika tidak ditemukan cukup bukti.
- Eksekusi Putusan
Putusan PTUN bersifat erga omnes, yakni berlaku secara umum dan wajib dihormati semua pihak, termasuk instansi pemerintahan. Bila putusan menyatakan KTUN batal atau tidak sah, maka secara hukum keputusan tersebut dianggap tidak pernah ada. PPK dan instansi wajib mencabut keputusan tersebut dan memulihkan hak vendor.
Jika instansi tidak melaksanakan putusan, vendor dapat mengajukan permohonan eksekusi ke PTUN dan bahkan mengadukan pelanggaran ini ke Ombudsman, Kementerian teknis, atau DPRD. Dalam beberapa kasus, pengabaian terhadap putusan PTUN juga dapat menjadi dasar pengaduan etik dan administratif terhadap pimpinan instansi.
VI. Risiko dan Dampak Bagi Vendor
Menggugat PPK atau instansi pemerintah di pengadilan, meskipun merupakan hak vendor yang sah secara hukum, tetap menyimpan sejumlah konsekuensi yang patut dipertimbangkan secara matang. Tidak semua vendor siap menghadapi dampak hukum, manajerial, maupun reputasional yang muncul sebagai efek samping dari proses gugatan tersebut.
- Relasi Bisnis Terganggu: Salah satu dampak yang paling umum adalah memburuknya hubungan kerja antara vendor dan instansi. Meskipun proses pengadaan seharusnya netral dan berdasarkan evaluasi objektif, dalam praktiknya dinamika hubungan personal dan persepsi terhadap “vendor penggugat” bisa menciptakan iklim kerja yang tidak sehat. Di beberapa daerah, vendor yang pernah menggugat bisa mengalami kesulitan menembus tender berikutnya karena dianggap “bermasalah” atau “tidak kooperatif”, meskipun itu tidak dinyatakan secara resmi.
- Biaya Litigasi Tinggi: Proses gugatan PTUN tidak gratis dan memerlukan sumber daya internal yang signifikan. Biaya perkara, jasa pengacara, biaya notaris, dan waktu staf manajerial untuk menyiapkan dokumen adalah beban yang harus ditanggung vendor. Dalam kasus gugatan atas kontrak bernilai miliaran rupiah, biaya hukum bisa mencapai puluhan juta, dan tidak semua vendor memiliki anggaran cadangan untuk proses ini.
- Reputasi Terganggu: Meski sah menggugat, vendor tetap berisiko mendapat label “troublemaker” di mata pasar, terutama jika kasus menjadi konsumsi media atau diumumkan di situs LPSE. Bahkan vendor yang menang pun bisa terkena stigma sebagai penyebab keributan administratif, bukan sebagai mitra konstruktif. Risiko reputasi ini sangat nyata, khususnya bagi vendor baru atau skala UMK yang masih membangun kepercayaan di lingkungan pemerintah.
- Ketidakpastian Hasil: Tidak ada jaminan bahwa gugatan akan dimenangkan vendor. PTUN bersifat menguji legalitas administratif, bukan kesalahan substansi teknis pekerjaan. Banyak gugatan ditolak karena tidak memenuhi syarat KTUN, dalilnya lemah, atau bukti tidak lengkap. Artinya, vendor bisa mengeluarkan waktu dan biaya besar tanpa mendapatkan hasil yang sepadan, bahkan bisa menghadapi gugatan balik dari pihak instansi jika tuduhan terbukti tidak berdasar.
- Dampak Operasional: Waktu manajer proyek, legal officer, dan direktur operasional bisa tersita untuk urusan pengadilan, padahal proyek lain masih berjalan. Selain itu, vendor bisa kehilangan fokus pada tender baru karena terganggu konflik yang belum selesai. Bagi perusahaan kecil, hal ini bisa mengganggu cashflow atau bahkan memperburuk neraca keuangan.
Oleh karena itu, vendor yang mempertimbangkan untuk menggugat PPK harus terlebih dahulu melakukan kalkulasi risiko secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan emosi atau persepsi ketidakadilan semata. Pendekatan berbasis data, konsultasi hukum, dan pertimbangan reputasi sangat penting untuk meminimalisir dampak jangka panjang.
VII. Strategi Persiapan dan Mitigasi
Agar vendor dapat menghadapi potensi sengketa dan kemungkinan menggugat PPK secara efektif, diperlukan serangkaian strategi proaktif yang menyangkut dokumentasi, tata kelola proyek, hingga kesiapan legal. Langkah-langkah berikut dapat membantu vendor meminimalkan risiko sekaligus memperkuat posisi jika harus memasuki ranah hukum:
- Dokumentasi lengkap: Setiap korespondensi, surat menyurat, email, notulen rapat, laporan kemajuan, dokumen kontrak, addendum, dan jaminan harus tersimpan rapi dan mudah diakses. Ini menjadi fondasi utama pembuktian di PTUN. Dalam praktiknya, vendor yang kalah bukan karena argumen lemah, tapi karena kurang bukti tertulis. Gunakan sistem manajemen dokumen berbasis cloud agar data tidak hilang atau rusak.
- Simulasi legal: Sebelum menggugat, vendor disarankan melakukan audit hukum internal terhadap kasus yang dihadapi. Apakah keputusan PPK bersifat KTUN? Apakah ada pelanggaran regulasi yang nyata? Lakukan simulasi gugatan dengan penasihat hukum agar bisa mengukur kekuatan dan kelemahan kasus. Audit ini juga penting untuk memperkirakan biaya, durasi, dan peluang menang.
- Konsultasi dini: Sebelum kontrak ditandatangani, vendor sebaiknya mengidentifikasi pasal-pasal berpotensi konflik-seperti termin pembayaran, pengenaan denda, dan klausul pemutusan sepihak. Jika perlu, lakukan negosiasi agar pasal tersebut adil dan tidak menimbulkan ruang tafsir yang merugikan. Langkah ini penting karena sebagian sengketa muncul dari pasal kontrak yang tidak jelas atau timpang.
- Compliance internal: Vendor perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani konflik proyek, mulai dari pemberian somasi, eskalasi ke atasan PPK, hingga kapan harus menggugat ke PTUN. SOP ini melatih kedisiplinan vendor untuk tetap berada dalam koridor hukum dan menjaga komunikasi formal.
- Pendampingan advokat: Dalam sengketa administratif, pemahaman terhadap UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, hukum kontrak, dan Perpres PBJ sangat penting. Vendor disarankan menggandeng penasihat hukum yang memahami pengadaan barang/jasa. Pendampingan ini tidak hanya soal gugatan, tapi juga membantu vendor memilih instrumen hukum yang paling tepat: somasi, keberatan, atau langsung PTUN.
VIII. Studi Kasus: Vendor vs PPK
Dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, tidak sedikit terjadi ketegangan antara vendor (penyedia) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Dua studi kasus berikut memperlihatkan bahwa meskipun posisi PPK sangat dominan dalam struktur kontraktual, bukan berarti keputusan mereka tidak bisa digugat atau dikesampingkan melalui jalur hukum jika terbukti melanggar ketentuan.
Kasus 1: Pembatalan Kontrak Tanpa Alasan Sah
CV Logistik Nusantara adalah penyedia yang memenangkan tender pengadaan barang logistik untuk kegiatan darurat di sebuah dinas daerah. Nilai kontraknya mencapai Rp800 juta dan proses pengiriman telah mencapai sekitar 70% volume barang sesuai jadwal dan spesifikasi. Namun, secara tiba-tiba, PPK memutuskan untuk mengakhiri kontrak secara sepihak. Tidak ada pemberitahuan tertulis sebelumnya, tidak pula disertai penjelasan teknis atau administratif yang menjadi dasar pemutusan hubungan kontraktual. Lebih buruk lagi, jaminan pelaksanaan yang sebelumnya diserahkan oleh vendor turut dicairkan tanpa komunikasi apa pun.
CV Logistik Nusantara segera merespons dengan melayangkan somasi secara tertulis, meminta penjelasan, dan menuntut pemulihan hak. Karena tidak memperoleh jawaban, vendor akhirnya menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan membawa bukti somasi, dokumen kontrak, bukti pengiriman, dan bukti komunikasi sebelumnya. Hasil putusan PTUN menyatakan bahwa tindakan PPK bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 dan asas-asas pemerintahan yang baik. Putusan pengadilan memerintahkan pencairan pembayaran termin yang belum disalurkan, pengembalian nama baik vendor (termasuk pencabutan status blacklist), serta teguran administratif kepada PPK bersangkutan.
Kasus ini menunjukkan bahwa vendor memiliki peluang untuk memperoleh keadilan apabila dapat menyajikan bukti kuat dan menunjukkan bahwa PPK telah menyalahgunakan kewenangan atau bertindak di luar ketentuan hukum dan kontrak.
Kasus 2: Keterlambatan Pembayaran Melampaui Jangka Waktu
PT Teknologi A mendapatkan kontrak pengembangan aplikasi e-budgeting dengan nilai Rp1,2 miliar. Proyek berhasil diselesaikan sesuai jadwal. Setelah dilakukan serah terima pekerjaan melalui dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima), pihak penyedia menunggu pembayaran termin akhir sesuai yang dijanjikan dalam kontrak. Namun setelah lewat lebih dari 60 hari, pembayaran tak kunjung dilakukan. PPK beralasan bahwa ada kekurangan dokumen yang harus dipenuhi vendor, meskipun dalam kontrak tidak diatur secara eksplisit mengenai dokumen tambahan tersebut.
Vendor melayangkan somasi sebanyak tiga kali namun tidak mendapat tanggapan. Akhirnya, vendor menyampaikan pengaduan resmi ke Ombudsman Republik Indonesia serta unit pengaduan internal LKPP. Hasil mediasi menemukan bahwa tidak ada dasar hukum yang sah atas penundaan pembayaran. Ombudsman kemudian merekomendasikan pencairan dana disertai bunga keterlambatan sesuai ketentuan Perpres No. 12 Tahun 2021 pasal 53 ayat (5), yang menyebutkan bahwa pembayaran pekerjaan harus dilakukan paling lambat 30 hari kerja setelah BAST.
Dari kedua kasus ini, dapat disimpulkan bahwa PPK tidak berada di atas hukum. Ketika tindakan mereka menyimpang dari regulasi dan merugikan pihak lain secara nyata, maka mekanisme gugatan administratif, mediasi, hingga litigasi formal dapat ditempuh oleh vendor, selama disertai bukti sah dan prosedur yang dilalui secara tepat.
IX. Kesimpulan
Secara konseptual dan yuridis, hubungan antara vendor dan PPK diatur dalam perikatan hukum yang tertuang dalam kontrak pengadaan. Kontrak ini bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan sumber hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Ketika salah satu pihak, dalam hal ini PPK, mengambil tindakan sepihak yang melanggar substansi kontrak atau prinsip pengadaan yang baik, maka vendor memiliki hak hukum untuk melakukan pembelaan, bahkan sampai pada upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, peradilan perdata, atau lembaga pengawas seperti Ombudsman.
Namun demikian, proses hukum ini bukan tanpa tantangan. Vendor harus menyiapkan bukti-bukti otentik seperti kontrak asli, BAST, bukti pengiriman atau pelaksanaan pekerjaan, bukti komunikasi seperti email dan surat resmi, serta dokumentasi somasi atau keberatan. Tanpa dokumentasi yang lengkap dan jelas, posisi vendor akan lemah di hadapan hukum. Oleh karena itu, dalam setiap proses pengadaan, vendor harus menjalankan fungsi administratif secara rapi dan disiplin, termasuk menyimpan semua dokumen penting dan mengarsipkan komunikasi dengan pejabat pengadaan.
Selain itu, risiko reputasi juga perlu diperhitungkan. Meski secara hukum vendor berada di posisi benar, keterlibatan dalam sengketa hukum dengan instansi pemerintah dapat menimbulkan citra yang kurang menguntungkan di mata publik dan rekan bisnis. Maka dari itu, vendor sebaiknya mengutamakan upaya mediasi dan jalur administratif terlebih dahulu sebelum masuk ke litigasi terbuka.
Pada akhirnya, vendor harus memahami bahwa mereka bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga bagian dari ekosistem tata kelola yang sehat. Kontrak harus dibaca dengan cermat, dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dan bila perlu-dipertahankan melalui mekanisme hukum yang sah demi menjaga keadilan dan profesionalisme dalam pengadaan publik.