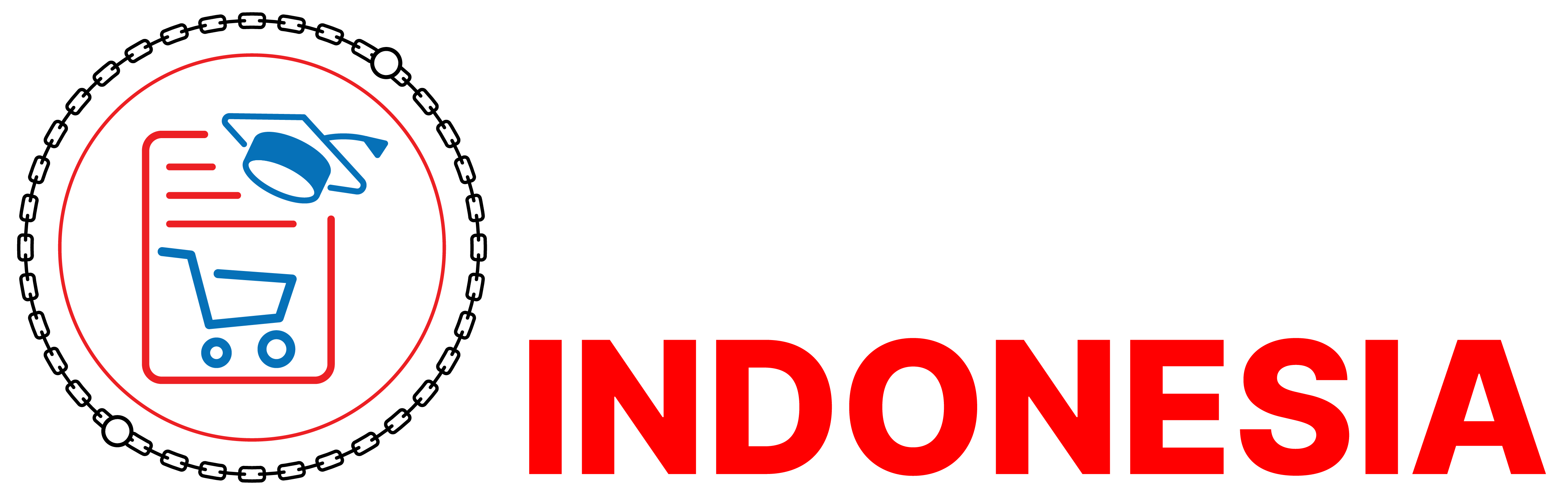Pendahuluan
Dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa, penyedia (vendor) dituntut tidak hanya menawarkan produk atau layanan berkualitas, tetapi juga mematuhi seluruh ketentuan administratif, teknis, dan etika yang diatur dalam regulasi. Sayangnya, tidak sedikit penyedia yang terjebak pada pelanggaran-baik sengaja maupun tidak-sehingga dikenakan sanksi yang bisa berdampak serius: mulai dari denda administratif, pemutusan kontrak, hingga blacklist yang mencegahnya ikut tender dalam kurun waktu tertentu. Artikel ini akan menguraikan secara komprehensif jenis-jenis sanksi yang biasa dikenakan kepada penyedia, mengidentifikasi penyebab umum pelanggaran, serta memberikan rekomendasi mitigasi agar vendor dapat tetap beroperasi dengan aman dan profesional.
1. Landasan Hukum Sanksi dalam Pengadaan
Landasan hukum sanksi terhadap penyedia barang/jasa pemerintah tidak hanya menjadi instrumen pengawasan, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah dan penjamin integritas proses pengadaan. Regulasi yang mengatur pemberian sanksi bersifat hierarkis, mulai dari tingkat peraturan presiden, peraturan lembaga, hingga undang-undang.
Pertama, Peraturan Presiden (Perpres) No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang kemudian diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021, merupakan kerangka hukum utama. Di dalamnya dijelaskan dengan rinci kewajiban, hak, larangan, dan konsekuensi hukum bagi penyedia yang melanggar prinsip-prinsip pengadaan. Pasal-pasal dalam Perpres ini memberikan dasar hukum yang sah bagi panitia atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menjatuhkan sanksi administratif dan mengusulkan blacklist.
Selanjutnya, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memuat Standar Dokumen Pengadaan (SDP), termasuk Prosedur Evaluasi dan Pelaksanaan Tender. Peraturan ini memberikan pedoman teknis operasional terkait klarifikasi, negosiasi, serta ketentuan evaluasi kinerja. Di dalamnya dijelaskan pula bagaimana penyedia dapat dinyatakan wanprestasi dan dijatuhi sanksi berdasarkan temuan evaluasi teknis atau administrasi.
Dari sisi pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi payung hukum apabila ditemukan unsur-unsur penyuapan, gratifikasi, kolusi, atau mark-up harga. Penyedia yang terbukti menyuap pejabat pengadaan atau memalsukan dokumen dapat dikenakan hukuman pidana yang berat, termasuk pidana penjara dan denda miliaran rupiah.
Terakhir, bagi pengadaan yang bersumber dari anggaran keuangan negara, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) juga turut mengatur mekanisme pengadaan swakelola, belanja langsung, atau sourcing dengan ketentuan pelaporan dan sanksi tersendiri jika penyedia tidak memenuhi komitmen kontraktual.
Dengan demikian, sistem hukum yang mengatur sanksi kepada penyedia merupakan jaring berlapis yang tidak hanya melindungi proses pengadaan dari praktik tidak etis, tetapi juga menjamin akuntabilitas dan efektivitas penggunaan APBN/APBD secara menyeluruh.
2. Kategori Utama Sanksi
Sanksi terhadap penyedia dalam pengadaan barang/jasa terbagi dalam tiga kategori besar: administratif, komersial, dan hukum. Masing-masing kategori memiliki mekanisme pemicu, tingkat dampak, dan ruang penyelesaian yang berbeda.
2.1 Sanksi Administratif
Sanksi administratif merupakan jenis sanksi yang paling umum dikenakan, terutama dalam tahap evaluasi atau pelaksanaan kontrak. Bentuk paling ringan adalah diskualifikasi, yaitu penyedia gugur dari proses lelang karena dokumen tidak lengkap, tidak sah, atau tidak sesuai format. Misalnya, penyedia mengunggah NPWP atas nama entitas yang berbeda dari nama badan usaha yang mendaftar.
Pemotongan Jaminan Pelaksanaan dapat dilakukan jika penyedia wanprestasi di tengah pelaksanaan proyek, misalnya tidak memulai pekerjaan dalam waktu yang ditentukan. Panitia berhak mengeksekusi sebagian atau seluruh nilai jaminan tersebut.
Sanksi administratif paling berat adalah blacklisting, yaitu pencantuman nama penyedia dalam Daftar Hitam Nasional (DHP) yang dikelola oleh LKPP. Dalam praktiknya, sanksi ini dijatuhkan jika vendor melakukan pelanggaran serius seperti memalsukan dokumen, gagal menyelesaikan pekerjaan tanpa alasan sah, atau terbukti bekerja sama secara ilegal dengan panitia. Durasi blacklist bervariasi, umumnya 1 hingga 5 tahun, dan berlaku lintas kementerian/lembaga dan pemda.
2.2 Sanksi Komersial
Sanksi komersial berkaitan dengan konsekuensi finansial yang diderita penyedia karena kegagalan kinerja. Salah satu yang paling sering diterapkan adalah denda keterlambatan, di mana penyedia harus membayar sejumlah persen dari nilai kontrak setiap harinya jika melampaui batas waktu pelaksanaan tanpa alasan force majeure.
Selain itu, panitia dapat menerapkan retensi pembayaran, yakni menahan sebagian pembayaran (misalnya 10%) hingga penyedia membuktikan bahwa seluruh pekerjaan telah memenuhi spesifikasi teknis dan administratif.
Sanksi komersial juga mencakup pengembalian kelebihan bayar, biaya pemulihan kerusakan, atau pengganti pekerjaan oleh pihak ketiga dengan biaya penyedia jika vendor tidak mampu menyelesaikan tugasnya.
2.3 Sanksi Hukum
Sanksi hukum dikenakan jika terdapat indikasi pelanggaran hukum berat. Ini mencakup dua jenis:
- Perdata, di mana penyedia digugat karena wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara. Contohnya, penyedia tidak membayar pajak atau retribusi meski sudah dicairkan dalam anggaran.
- Pidana, jika penyedia terbukti menyuap pejabat, menggelapkan dana proyek, atau memalsukan dokumen dalam rangka memenangkan tender. Dalam hal ini, proses dilimpahkan kepada aparat penegak hukum seperti BPK, KPK, atau kejaksaan.
Sanksi hukum membawa konsekuensi sangat serius, termasuk pembekuan aset, pencabutan izin usaha, hingga hukuman penjara bagi direksi.
3. Penyebab Umum Penerapan Sanksi
Berbagai bentuk sanksi biasanya tidak datang tiba-tiba, tetapi merupakan respons terhadap pelanggaran tertentu yang dapat diidentifikasi. Berikut beberapa penyebab paling umum yang memicu sanksi kepada penyedia:
3.1 Ketidaksesuaian Dokumen Administrasi
Penyebab sanksi paling awal dan umum terjadi pada tahap evaluasi administrasi adalah ketidaksesuaian atau kekurangan dokumen:
- Dokumen yang sudah kedaluwarsa, seperti SBU, SIUJK, atau Sertifikat ISO, akan langsung menggugurkan penyedia dari proses tender. Panitia tidak memiliki kewajiban menunggu atau mengingatkan vendor untuk memperbarui dokumen.
- Dokumen palsu atau tidak valid adalah pelanggaran serius. Contoh: sertifikat tenaga ahli (SKA) yang ternyata tidak dikeluarkan oleh LSP yang sah, atau dokumen akta perusahaan yang tidak sesuai dengan data AHU online.
- Kesalahan teknis saat unggah dokumen ke LPSE juga bisa berdampak fatal, seperti nama file salah, format tidak sesuai PDF/A, atau dokumen rusak (corrupt), sehingga tidak bisa dibuka oleh panitia.
3.2 Kegagalan Kinerja dan Deliverable
Ketika proyek berjalan, vendor dituntut memenuhi spesifikasi teknis sesuai kontrak dan BoQ (Bill of Quantity). Kegagalan dalam aspek ini bisa berupa:
- Produk/jasa tidak sesuai spesifikasi, misalnya menyuplai AC kapasitas 1 PK padahal dalam spesifikasi tertulis minimal 2 PK.
- Pekerjaan cacat atau gagal fungsi (misal: bangunan retak dalam waktu 3 bulan sejak diserahterimakan) yang mengindikasikan kualitas buruk atau ketidaksesuaian metode.
- Keterlambatan pekerjaan, terutama jika melebihi toleransi kontrak (misal: >20 hari) tanpa permohonan resmi atau tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.
3.3 Praktik Tidak Etis dan Korupsi
Ini adalah jenis pelanggaran yang dampaknya paling luas dan menjadi perhatian utama pemerintah. Praktik tidak etis meliputi:
- Gratifikasi atau suap kepada panitia: baik berupa uang, hadiah, maupun fasilitas.
- Kolusi antar vendor, seperti menetapkan harga bersama (price fixing) atau berbagi wilayah tender (bid rigging), melanggar prinsip kompetisi sehat.
- Manipulasi laporan teknis atau keuangan, seperti menggelembungkan harga unit, mencantumkan bahan tidak digunakan dalam laporan pembayaran, atau merekayasa berita acara serah terima.
3.4 Keterlambatan dan Force Majeure yang Tidak Dilaporkan
Kadang keterlambatan memang tidak dapat dihindari karena bencana alam, larangan impor, atau gangguan rantai pasok. Namun penyedia tetap diwajibkan:
- Mengajukan klaim force majeure secara resmi dan tepat waktu, disertai dokumen pendukung dan pemberitahuan tertulis kepada PPK.
- Mengikuti mekanisme adendum atau rescheduling kontrak secara formal, bukan hanya dengan komunikasi lisan.
Gagal menjalankan prosedur ini membuat keterlambatan tetap dianggap sebagai wanprestasi, meskipun penyebabnya objektif.
4. Dampak Sanksi terhadap Vendor
Sanksi yang dijatuhkan kepada penyedia barang/jasa tidak hanya menimbulkan kerugian jangka pendek, tetapi juga berimplikasi sistemik terhadap keberlangsungan bisnis, reputasi, dan peluang usaha di masa depan. Tiga dampak utama yang paling dirasakan vendor antara lain adalah dampak finansial, reputasi, dan akses pasar.
4.1. Kerugian Finansial Langsung
Vendor yang dikenai sanksi seperti denda keterlambatan atau pemotongan retensi akan mengalami tekanan terhadap arus kas. Misalnya, dalam kontrak senilai Rp2 miliar dengan klausul denda 1‰ per hari keterlambatan, penyedia yang terlambat 30 hari akan menanggung denda Rp60 juta. Jumlah tersebut belum termasuk potensi pengurangan jaminan pelaksanaan dan biaya remediasi akibat pekerjaan yang tidak sesuai.
Dalam kasus lain, penyedia dapat mengalami pembekuan pembayaran sebagian atau seluruhnya, hingga terjadi penyelesaian permasalahan. Hal ini sangat berdampak bagi vendor skala kecil-menengah yang mengandalkan pembayaran termin untuk operasional berikutnya. Aliran dana terganggu, proyek lainnya ikut terhambat, dan keuangan internal perusahaan bisa goyah.
4.2. Penurunan Reputasi Bisnis
Dalam ekosistem pengadaan yang transparan dan saling terkoneksi seperti LPSE, informasi mengenai vendor yang mendapat sanksi dapat dengan mudah diketahui oleh instansi lain. Hal ini menyebabkan penurunan kepercayaan yang signifikan dari para pengguna jasa dan klien lainnya.
Vendor yang masuk dalam daftar hitam nasional tidak hanya terhalang dari proyek pemerintah, tetapi juga akan dipertimbangkan sebagai “berisiko” oleh BUMN, institusi donor, atau perusahaan swasta besar yang menggunakan database reputasi sebagai salah satu indikator seleksi. Bahkan jika sanksinya administratif ringan, citra profesional penyedia tetap akan terdampak.
4.3. Tertutupnya Akses Pasar dan Tender
Sanksi blacklist nasional, misalnya, akan memblokir vendor dari seluruh peluang tender pemerintah dan BUMN selama masa sanksi berlaku. Hal ini menciptakan isolasi pasar, terutama bagi perusahaan yang bergantung pada proyek-proyek pemerintah sebagai tulang punggung pendapatan.
Selain itu, proses pembatalan tender oleh panitia karena kecurigaan terhadap legalitas penyedia dapat memicu audit eksternal, baik dari APIP maupun BPK. Jika terbukti melanggar peraturan, penyedia bisa dikeluarkan dari daftar rekanan (vendor list) secara permanen. Dalam jangka panjang, ini akan mengurangi kredibilitas vendor saat menjalin kerja sama bisnis baru, baik di dalam maupun luar negeri.
5. Prosedur Pengajuan Keberatan (Sanggah)
Penyedia yang merasa dirugikan oleh keputusan panitia tender, terutama dalam hal sanksi administratif, memiliki hak untuk mengajukan sanggahan secara resmi. Mekanisme ini penting dalam menjamin keadilan, objektivitas, dan transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa.
5.1. Tenggat Waktu dan Tata Cara Pengajuan
Menurut Perpres No. 16/2018 dan turunannya, pengajuan sanggahan harus dilakukan maksimal 5 hari kerja sejak diumumkannya hasil evaluasi atau pemberitahuan sanksi. Sanggahan dapat disampaikan melalui sistem LPSE atau dikirim ke unit pengadaan dengan tembusan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan inspektorat internal.
Sanggahan harus disusun secara sistematis, berisi:
- Pernyataan keberatan atas keputusan panitia
- Argumentasi hukum dan administratif yang mendukung klaim
- Bukti dokumen pendukung (misal: akta perbaikan, sertifikat asli, kronologi proyek)
- Permintaan evaluasi ulang atau pembatalan keputusan
Sanggahan yang tidak dilengkapi bukti atau disampaikan di luar tenggat waktu akan ditolak secara administratif tanpa ditinjau substansi isinya.
5.2. Proses Evaluasi dan Mediasi
Setelah sanggahan masuk, panitia bersama Pokja dan PPK melakukan evaluasi ulang terhadap dokumen, mengundang pihak vendor jika diperlukan, dan menelaah ulang keputusan yang dijadikan dasar sanksi.
Jika ditemukan kesalahan panitia atau bukti baru yang sah dari vendor, maka panitia berwenang mencabut sanksi dan mengembalikan status vendor ke posisi semula. Dalam kasus lebih kompleks, sanggahan dapat diteruskan ke Tim Sanggah di instansi atasan atau bahkan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) untuk ditindaklanjuti.
Namun, jika sanggahan dianggap tidak berdasar atau terindikasi sebagai taktik untuk menunda proses, maka permohonan akan ditolak dan sanksi tetap dijalankan.
5.3. Implikasi Hukum
Penting dicatat, pengajuan sanggah tidak menghentikan sementara sanksi yang sedang dijalankan. Vendor tetap tidak bisa mengikuti tender selama masa sanggah berlangsung. Oleh karena itu, penyusunan sanggahan harus dilakukan secara serius dan berbasis data hukum yang kuat agar tidak memperpanjang dampak bisnis.
6. Studi Kasus: Vendor Terkena Sanksi
Studi kasus memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana sanksi dijatuhkan, serta pelajaran yang dapat diambil vendor lain agar tidak mengulangi kesalahan serupa.
6.1. Vendor X: Diskualifikasi karena Sertifikat ISO Palsu
Dalam tender pengadaan sistem IT senilai Rp8 miliar di salah satu kementerian, Vendor X melampirkan sertifikat ISO 27001 untuk keamanan informasi. Setelah evaluasi administrasi, panitia memverifikasi sertifikat tersebut ke situs resmi badan sertifikasi dan mendapati bahwa sertifikat tersebut tidak tercantum dalam database internasional.
Panitia melakukan klarifikasi, namun Vendor X tidak dapat menunjukkan bukti keaslian atau dokumen pendukung. Akibatnya, vendor didiskualifikasi, jaminan penawaran ditarik, dan kasusnya dilaporkan ke inspektorat. Hasil investigasi menyatakan Vendor X melakukan pemalsuan, dan akhirnya dimasukkan ke dalam blacklist selama 2 tahun. Proyek akhirnya dimenangkan oleh vendor lain yang meski menawarkan harga sedikit lebih tinggi, namun dokumennya sah.
Pelajaran:
- Verifikasi dokumen tidak boleh disepelekan
- Jangan tergoda menggunakan dokumen palsu karena sanksinya berat
- Pastikan semua dokumen legal bersumber dari institusi resmi
6.2. Vendor Y: Denda Keterlambatan 1% per Hari
Vendor Y merupakan pemenang tender pembangunan fasilitas olahraga senilai Rp25 miliar. Dalam kontrak disebutkan bahwa setiap hari keterlambatan dikenakan denda 1‰ (satu permil) dari nilai kontrak. Proyek direncanakan rampung dalam 120 hari kalender.
Namun, karena vendor gagal melakukan pemesanan material sejak awal, terjadi keterlambatan suplai baja selama 25 hari. Vendor Y baru menyampaikan surat force majeure setelah pekerjaan mundur 15 hari, itupun tanpa bukti pendukung dari pemasok. Panitia menolak klaim keterlambatan sebagai force majeure dan menjatuhkan denda keterlambatan sebesar Rp625 juta.
Walau proyek tetap selesai dengan kualitas baik, Vendor Y mengalami kerugian finansial signifikan dan tertunda pembayaran 10% retensi selama 3 bulan hingga audit teknis selesai.
Pelajaran:
- Perencanaan logistik dan material sangat krusial
- Force majeure harus dibuktikan dan diajukan tepat waktu
- Keterlambatan memiliki dampak finansial yang besar, terutama untuk proyek bernilai tinggi
7. Rekomendasi Pencegahan dan Mitigasi
Agar vendor tidak terjerumus ke dalam pelanggaran yang berujung sanksi, perlu dibangun sistem pencegahan dan mitigasi risiko yang proaktif, sistematis, dan berkelanjutan. Pencegahan bukan hanya soal menghindari kesalahan, tetapi menciptakan tata kelola internal yang tangguh dan responsif terhadap dinamika pengadaan.
7.1. Audit Legalitas dan Kepatuhan Secara Berkala
Melakukan audit legalitas secara rutin (misalnya setiap 3-6 bulan) memungkinkan vendor memeriksa apakah semua dokumen penting-seperti NIB, SBU, SIUJK, NPWP, SKA, dan ISO-masih aktif, sah, dan sesuai dengan ketentuan tender terkini. Banyak vendor terdiskualifikasi hanya karena dokumen yang habis masa berlakunya atau perubahan struktur organisasi yang belum diperbarui di OSS.
Langkah audit ini sebaiknya menjadi bagian dari SOP internal, yang dijalankan oleh unit legal dan dikawal langsung oleh manajemen. Gunakan checklist berbasis dokumen LPSE dan e-Proc untuk memastikan kelengkapan.
7.2. Quality Assurance Sebelum Serah Terima
Kesalahan fatal yang menyebabkan denda dan retensi umumnya terjadi karena kelalaian menjelang penyerahan hasil pekerjaan. Oleh sebab itu, vendor perlu menerapkan sistem Quality Assurance (QA) dan Quality Control (QC) sebagai standar wajib sebelum setiap tahap serah terima.
Tim QA harus memastikan bahwa:
- Spesifikasi teknis sesuai dengan dokumen kontrak dan BoQ
- Pekerjaan lapangan sudah melewati uji kelayakan atau uji fungsi
- Semua dokumentasi serah terima, berita acara, dan bukti pendukung disiapkan lengkap
Pendekatan QA tidak hanya mencegah klaim kegagalan kinerja, tapi juga menjadi bukti pembelaan bila terjadi sengketa dengan panitia.
7.3. Sistem Whistleblowing Internal
Vendor juga harus membuka kanal pelaporan internal-yang disebut whistleblowing system (WBS)-untuk mencegah praktik tidak etis dari dalam. Banyak pelanggaran seperti kolusi, pemalsuan dokumen, dan suap justru berasal dari individu dalam perusahaan, bukan dari luar.
Dengan WBS, karyawan atau mitra bisa melaporkan dugaan pelanggaran secara anonim dan aman. Sistem ini perlu dilengkapi mekanisme tindak lanjut, sanksi internal, dan perlindungan pelapor agar efektif. Dalam jangka panjang, WBS juga meningkatkan budaya integritas perusahaan di mata publik dan pemberi kerja.
7.4. Asuransi Proyek dan Force Majeure
Untuk risiko yang tidak dapat dikendalikan (force majeure), vendor dapat menempuh pendekatan mitigasi melalui asuransi proyek. Asuransi ini mencakup perlindungan atas keterlambatan akibat bencana alam, pemogokan buruh, atau kerusakan alat berat yang berdampak signifikan terhadap jadwal proyek.
Vendor juga perlu menyusun protokol pelaporan force majeure dengan dokumentasi lengkap-misalnya surat dari BMKG untuk banjir atau surat resmi pemutusan pasokan dari vendor utama-agar klaim dapat diterima oleh panitia.
Selain itu, menyisipkan klausul force majeure dalam kontrak dan memahami batas toleransi waktu dapat menjadi kunci agar keterlambatan tidak serta merta dianggap sebagai wanprestasi.
8. Kesimpulan
Dalam ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah maupun swasta, sanksi terhadap penyedia bukanlah sekadar alat hukuman, tetapi merupakan instrumen penting dalam menjaga kedisiplinan, akuntabilitas, dan keadilan dalam persaingan usaha. Penerapan sanksi mencerminkan komitmen negara untuk membangun pengadaan yang transparan, berintegritas, dan bebas dari praktik manipulatif.
Dari sisi vendor, memahami ragam sanksi-administratif, komersial, hingga pidana-serta mengenali penyebab-penyebab umumnya seperti dokumen tidak sah, kegagalan kinerja, keterlambatan, dan pelanggaran etika, menjadi bekal utama dalam menghindari kesalahan fatal. Pencegahan lebih murah daripada pemulihan, dan reputasi lebih sulit dibangun daripada rusak.
Dengan membentuk sistem manajemen kepatuhan internal, mengadopsi praktik QA dan audit berkala, serta membudayakan etika bisnis melalui pelatihan dan whistleblowing system, vendor tidak hanya bisa menghindari sanksi, tetapi juga membangun keunggulan kompetitif jangka panjang. Hal ini penting, terlebih di era pengadaan digital dan keterbukaan data, di mana rekam jejak vendor menjadi bagian dari penilaian kelayakan di setiap tender.
Terakhir, vendor perlu melihat pengadaan bukan semata-mata ajang transaksi, tapi juga ruang reputasi. Ketekunan dalam menjaga legalitas, ketepatan waktu, dan komitmen terhadap kualitas akan membuka pintu tender lebih luas, memperbesar peluang menang, dan memperkuat keberlanjutan usaha secara menyeluruh.